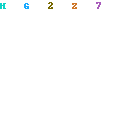Akhirnya, aku bersandar pada Subuh yang dingin, ketika benua yang biadab ini menggores namaku di atas selembar sejarah. Lalu memulai cerita dari setetes embun Subuh yang jatuh ke hulu. Kemudian yang tak begitu lama setelah itu, aku sudah merindukan pantai yang menjanjikan kehidupan nan jauh dari ketololan dan kebusukan yang selama ini menodai seluruh tubuhku.
Barangkali hanya ada satu pantaiku yang selalu menderu-derukan ombak. Tiada hentinya kemesraan diciumkan ke pantai, ombak-ombak berbuih yang hangat. Siang, malam, bahkan tak ada hentian sejenak untuk menghilangkan letih. Pun setiap hempasan adalah kekuatan yang maha dahsyat, hingga bebatuan itupun hancur bebenturan sesamanya.
Barangkali hanya ada satu pantaiku yang selalu menderu-derukan ombak. Tiada hentinya kemesraan diciumkan ke pantai, ombak-ombak berbuih yang hangat. Siang, malam, bahkan tak ada hentian sejenak untuk menghilangkan letih. Pun setiap hempasan adalah kekuatan yang maha dahsyat, hingga bebatuan itupun hancur bebenturan sesamanya.
Aku, setetes embun yang jatuh ke hulu, telah jauh melampaui perjalanan dari tebing-tebing yang curam. Saat aku masih dingin-dingin sejuk, merasai keberadaanku di tempat yang tinggi. Lalu aku meluncur dengan kekuatan deras, bersama buih-buih dan sisa-sisa kesejukan. Aku memang tak bisa mengalir tenang, beberapa turbulensi terbentuk, terpuntir, mengulang lagi perjalanan. Sebab semenjak itu sudah mulai membawa debu-debu, pasir dan material lain. Kesemuanya merupakan bekal yang kudapat di sepanjang perjalanan ini. Hulu yang curam itu membuatku harus berlari terburu-buru, hingga tak semua material sempat kubawa.
Setelah ada keberadaanku di hilir nanti, aku berharap perjalananku menjadi lebih tenang dan hening. Tak perlu lagi harus berdesak-desak di tebing yang curam dan menakutkan. Bekal hidupku pun sudah kian banyak, terlihat dari warna keruhku yang telah menghapus kepolosanku dulu.
Hilir ini memang tenang, tapi semakin banyak beban kubawa. Tidak tahu lagi masih berapa banyak harus dihanyutkan. Kinipun tibalah saatnya nasibku harus terbentur cadas keras. Arahku ke sana memang kian dekat. Belum juga kupunya kekuatan untuk mengalihkan arah dari cadas keras itu. Aku memang harus membenturnya, aku harus siap menghantamnya. Pengorbanan besar diantara pengorbanan-pengorbanan yang telah kulepaskan. Aku memang harus yakin bahwa cadas keras itu akan hancur oleh kekuatanku membenturnya. Tapi cukupkah kekuatanku selama ini? Yang kubawa hanyalah puing-puing kecil tak berarti.
Apakah aku masih boleh menangis bila terhempas? Percikan air mata akan jauh meloncat, tinggi dan lenyap menjadi butiran-butiran kecil.
Sungguh aku tak ingin melewati turbulensi-turbulensi hingga beberapa kali, berapa lagi harus berputar-putar di pusaran yang memusingkan. Sedangkan di belakang batu itu sudah ada sebuah muara menganga. Haruskah kulingkari batu besar ini sekali lagi dan sekali lagi?
Tapi di sana muara sungguh gagahnya. Aku sudah rindu dengan kecerahanmu, lambaian nyiurmu. Kelak aku akan menuju pantai yang berpasir halus dan lembut. Disanalah ombak lautan akan datang mencium pantai itu. Disanalah tampak, semangat yang tak terpadamkan laksana riaknya yang datang silih berganti, tiada henti. Seakan tiada jera, tiada lelah dan keluh kesah.
Begitulah, andaikata setetes embun yang telah menjadi air laut itu tahu harus bagaimana, maka ia tidak akan kembali membenahi selimut tidurnya ketika fajar telah menyingsing.
Nah! Masih seonggok sampah jugalah aku; pengembara terpenjara yang hanya bisa berdoa, berharap, tanpa tahu dimana ia telah menyimpan kitab-kitab yang berisi nyanyian Cinta masa lalu. Dengan begitu, meskipun benua-benua yang jauh itu mengirim nyanyian peradaban yang gaduh sekalipun, aku yakin bahwa aku akan beranjak tua dan hanya bersandar pada kesunyian. Tak punya sejarah, tak punya nabi, hanya sajak-sajak luka yang kugoreskan di pohon-pohon.
Jadi hitam kelam jualah yang menungguku di ujung senja: ujung pengembaraan setiap manusia.